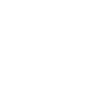Suara Keheningan Sang Profesor Pareira: „Sukacitaku ialah belajar dengan sukacita“

Suara Keheningan | Inosensius I. Sigaze
Sebuah nama tidak disebut jika tidak pernah ada, sebuah gambar tidak dipajang jika tidak berkesan, satu suara tidak akan pernah terdengar, jika tidak bergema. Catatan dan cerita terbongkar tiba-tiba dan tersebar ke banyak dinding media, ketika Sang Profesor Pareira itu pergi untuk selama-lamanya. Kenangan lama bersamanya dibuka perlahan-lahan, bahkan diskusi bermunculan. Keinginan mengumpulkan karya dan kisahnya muncul begitu kuat sampai tidak tahu harus mulai dari mana. Karena itu, tulisan ini juga merupakan serpihan kisah bersamanya untuk dikenang dan direnungkan.
Sang Guru yang tidak pernah berhenti belajar
Tiga hari sudah berlalu dari cerita pertama tentang kepergian Sang Profesor Kitab Suci untuk selamanya. Harum namanya terasa tidak pernah pudar. Suara-suara orang yang pernah mengenalnya terdengar satu per satu. Pengakuan murid pertama yang kini telah menjadi Uskup Keuskupan Malang perlu dikenang terus: „Saya bersyukur, karena saya menjadi murid pertama setelah Romo Pareira menyelesaikan Doktoratnya di Roma pada tahun 1975“ (Kata Pembuka Mgr. Pidyarto dalam Misa Requiem Romo Pareira) Kata-kata dari murid pertama ini bukan saja suatu ungkapan sukacita karena pernah belajar dari Sang Guru itu, tetapi juga suatu kesaksian tentang dia yang berjasa dan memberikan terang ilmu berbasiskan Kitab Suci sekian lama hingga sekarang. Sang guru yang sabar mengajar dan terus menuntun hingga suatu waktu keduanya sama-sama menjadi guru. Cerita ini bukan cerita biasa bahwa Guru dan Murid sama-sama menjadi Profesor Kitab Suci. Keduanya seperti ada dalam suatu lingkaran perjanjian, yang tua mengenal dan mendalami khusus Perjanjian Lama, sedangkan yang muda mengenal dan mendalami Perjanjian Baru. Betapa indah dan lengkapnya buku-buku Perjanjian itu dipelajari oleh dua Karmelit itu.
Sukacitaku ialah belajar dengan sukacita
Lembaran Kitab Perjanjian Lama telah dibuka, dibaca dan di tafsir hingga halaman terakhir oleh Sang Pencinta Firman itu. Adakah suatu kebetulan antara motto „Sukacitaku ialah belajar dengan sukacita“ dipilihnya? Jawabannya jelas-jelas „tidak.“ Tidak ada satupun yang tahu, mengapa motto itu ditulis dalam seluruh hidupnya. Saya baru mendengar motto itu setelah Romo Pareira meninggal dunia. Mengapa begitu terlambat bagi saya untuk tahu dan meminta ceritanya tentang „sukacitaku ialah belajar dengan sukacita?“ Tidak ada yang bisa disalahkan. Mungkin ini kesempatan untuk suatu keberagaman cara pandang dan terbukanya ruang diskusi tentang Sang Sukacita itu. Romo Pareira adalah sosok yang suka berdiskusi. Mungkin saja Romo Pareira memiliki gagasan tentang konfrontasi yang membuka ke arah perkembangan dan perubahan. Sorotan diskusi pada sesi-sesi terakhir sebelum kematiannya, terlihat bagaikan suatu percampuran ide yang tidak biasanya. Meskipun demikian, nada kegembiraan, sukacita dalam membahas perbedaan-perbedaan yang ada dalam komunitas, masyarakat dan dunia selalu bisa dikatakan nikmat. Kenikmatan membahas dan berdiskusi itu akhirnya sampai pada halaman terakhir, yaitu kata penutup: „Ia pergi dalam keheningan jiwa sang pencinta Firman“.
Lagu sukacita pada hari terakhir
Kematiannya bagaikan menulis kata penutup dalam sebuah buku. Buku kehidupannya diakhiri dengan kata sukacita. Pada Ekaristi hari terakhir yang dirayakannya, Romo Pareira dalam kata pembukanya mengatakan: „Hari ini adalah hari terakhir kita menyanyikan lagu sukacita, besok sudah tidak lagi.“ (7 Januari 2021 | Kesaksian dari Sofi dari ruang Sakristi). Tidak bisa dibayangkan bahwa hidupnya menjadi begitu dekat dengan Sabda. Kesesuaian antara kata-katanya, hidupnya dan Firman Tuhan sungguh terlihat sejalan. Dalam Buku Perjanjian Lama yang dikenal, dipelajari dan diimani Romo Pareira sebagai Firman Tuhan diakhiri dengan kata-kata ini: „…anggur yang bercampur dengan air adalah sedap rasanya dan menimbulkan kegembiraan yang nikmat, demikianpun kesenian menyusun kisah menyegarkan pendengaran para pembaca karangan. Dan dengan ini tamatlah sudah.“ (2 Makabe 15: 39). Terlihat kemiripan kata-kata terakhirnya (hari terakhir) dengan kata-kata terakhir Kitab Suci Perjanjian Lama (tamatlah sudah). Hubungan ini tidak berlebihan selain untuk menggambarkan betapa Romo Pareira sangat mencintai Kitab Suci. Dalam satu artikel untuk Suara Keheningan pada 1 Oktober 2011, Romo Pareira menulis tentang St. Theresia dari Kanak-kanak Yesus dan Cinta akan Kitab Suci. Kalimat awal dari tulisannya sebagai berikut: „St. Theresia dari Kanak-kanak Yesus atau Wajah Tersuci hidup pada zaman tidak ada Kitab Suci bagi kaum perempuan. Akan tetapi, sangat menarik bahwa dalam tulisan-tulisan St. Theresia ada 440 kutipan Perjanjian Lama dan 650 dari Perjanjian Baru baik secara tersurat maupun tersirat. Harus diakui luar biasa untuk seorang perempuan yang begitu muda dan hidup pada zaman ketika Kitab Suci merupakan buku yang tertutup bagi kaum perempuan.“ Dari kalimat ini, bisa dibayangkan cinta, perhatian dan ketelitian Romo Pareira dalam menghitung penggunaan teks Kitab Suci dalam tulisan St. Theresia dari Kanak-kanak Yesus. Kenyataan ini sangat menarik bahwa dalam tulisan-tulisannya, Theresia dari Kanak-kanak Yesus menggunakan teks Kitab Suci sejumlah 1.090 secara keseluruhan baik secara tersurat maupun tersirat.
Kesaksian dan kesesuaian antara iman, ilmu dan hidup
Romo Pareira tentu memiliki kedekatan spiritualitas dengan St. Theresia Kanak-kanak Yesus. Ia tidak hanya menghitung berapa banyak Teks Kitab Suci yang dikutip St. Theresia, tetapi Romo Pareira sendiri menggunakan Kitab Suci dalam tulisan-tulisannya. Sebagai bukti, saya pernah menghitung 158 Teks Kitab Suci yang digunakan Romo Pareira dalam bukunya „Mari Merayakan Ekaristi Dengan Indah.“ Padahal buku itu hanya 153 halaman. Sudah bisa dibayangkan berapa teks yang pernah digunakan selama hidupnya dan dalam semua tulisannya. Sungguh layak dan pantas, kalau dikatakan bahwa hidupnya itu adalah suatu „Kitab Suci.“ Kesatuan antara ilmu dan hidup itu adalah suatu kebenaran dan kesaksian yang tidak pernah mati. Oleh karena itu adalah kebenaran dan kesaksian yang berakar dalam Kitab Suci, dan ilmu yang dipelajari dengan sukacita, maka tidak berlebihan kalau dikatakan itu adalah kekudusan yang diwariskannya. Ia hidup dalam semangat mencintai Firman Tuhan. Dalam homili pada misa terakhirnya pada 7 Januari 2021, Romo Pareira mengatakan demikian: „ Jika kita mengatakan bahwa kita mencintai Allah, tetapi kita tidak bisa mencintai sesama kita yang benar-benar nyata di hadapan kita, maka itu adalah omong kosong.“ (Sofi: Koster Kayu tangan) Kata-kata itu tentu terinspirasi dari teks bacaan pada hari itu (1 Yohanes 4:19-5:4).
Hidup sebagai karya seni
Hidupnya telah menjadi sebuah karya seni. Sebuah karya seni yang dilukisnya tidak hanya dengan tinta dan warna khas ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan sukacita, tetapi juga hidup yang diperkaya dengan iman yang mendalam, cinta yang membara, dan harapan yang tidak tergoyahkan. Karya seninya muncul setelah kepergiannya. Sebuah karya seni yang dilukis kembali dari serpihan kata kenangan, dan catatan-catatan lepas. Karya itu seperti suara dalam keheningan. Suatu suara keheningan yang tercipta karena kehilangan sang guru tua yang berkobar-kobar seperti nabi Elia, tetapi juga suatu suara keheningan karena kerinduan akan figur yang bijaksana, rendah hati, tegas dan berwibawa.
Penutup
Tulisan ini merupakan satu ungkapan penghargaan dan terima kasih atas jasa Romo Pareira yang telah memberikan nama „suara keheningan“ pada tahun 2011. Dahulu Romo Pareira memberi nama itu, sekarang nama itu berubah jadi hidup dan suaranya mulai bergema dalam keheningan. Tentunya, suara itu bergema untuk menyanyikan lagu cinta tentang sang Guru yang hidupnya terbukti setia dan bersatu dengan Sabda.